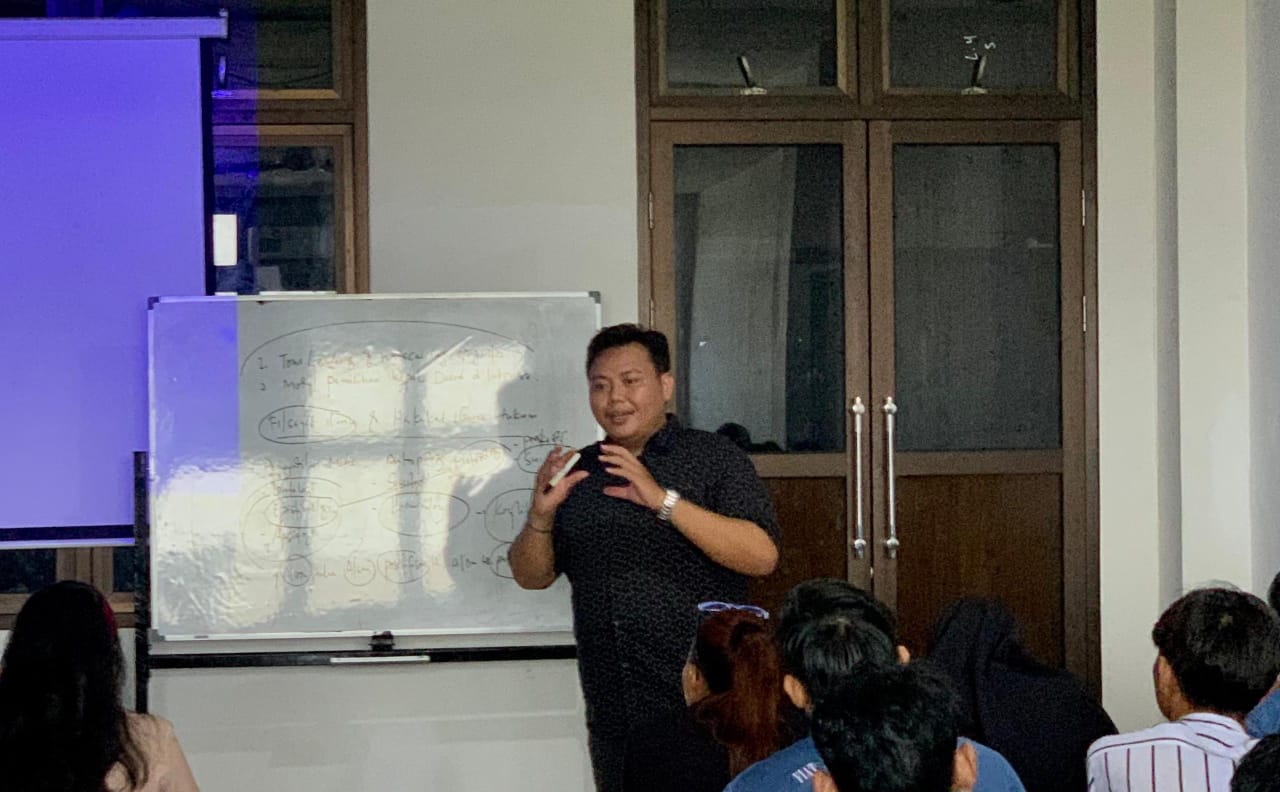
Ditulis Oleh: Ahmad Saripudin Nur, S.H., M.H (Kolumnis dan Peneliti Bidang Kebijakan Publik dan Demokrasi)
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional akhirnya berlangsung di Istana Negara pada 10 November 2025 kemarin. Ada sepuluh tokoh yang dinilai telah memberikan jasa dan sumbangsih besar, sehingga negara memandang perlu menganugerahkan penghargaan tertinggi itu. Secara eksistensial, jumlah Pahlawan Nasional bertambah menjadi 237 nama dan karena sedikit mereka akan terus diingat dan tercatat sebagaimana pepatah mengatakan, “sejarah hanya akan mengingat nama orang-orang besar.”
Namun, bagaimana jika diantara nama-nama itu masih menyisahkan luka yang masih terus menganga yang sejatinya secara moral sebuah bangsa masih mempertanyakan kredibilitas kepahlawanannya, apakah salah jika sebuah bangsa mempertanyakan bahwa pemberian gelar itu kontroversial ? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah suara-suara sumbang belaka, namun perlu dijawab seperti pendapat Prof. Zainal Arifin Mochtar agar tidak terjadi kekaburan makna seorang Pahlawan.
Faktanya SK Presiden telah dikeluarkan, saya tidak memiliki pretensi untuk membicarakan bagaimana keputusan presiden itu, tapi saya memiliki kepentingan untuk mengingatkan bahwa luka masa lalu masih belum disembuhkan dan oleh karena itu kita harus membicarakannya karena sejarah tidak boleh eksis dalam isolasi, bagaimanapun juga sejarah bersifat mengulang dirinya sendiri (the history is repeat itself).
Ingatan kolektif bangsa itu merujuk pada beberapa peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu 60 tahun terakhir tepatnya dimulai pada tahun 1965-1998 dimana peristiwa-peristiwa itu terjadi pembunuhan massal (mass killing), penghilangan paksa (force disappeared), penculikan dan penyiksaan (abduction and torture), pelanggaran berat hak asasi manusia (gross violance of human rights) hingga kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity).
Jika kita membaca sejarah, tidak akan ada yang menyangkal bahwa peristiwa-peristiwa terjadi ? faktanya waktu 60 tahun itu terasa masih baru karena ingatan kolektif itu sangat basah di ingatan. Mereka yang menjadi korban baik itu penyiksaan, penghilangan, penculikan, penembakan misterius, hingga pembunuhan massal menyimpan luka yang belum kering. Mengangkat tokoh yang secara langsung/tidak langsung terlibat dalam peristiwa itu bagaikan mengkoyak nurani dan moral bangsa bak menabur garam diatas sebuah luka.
Tidak terhitung jumlah nyawa yang menjadi korban, Amnesti International menyebutkan angka korban yang mencapai sekitar 500.000 hingga 1 juta orang. Baru-baru ini dalam rentang waktu 32 tahun orde baru Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyebutkan beberapa peristiwa penting seperti pembantaian massal (1965-1966), Tragedi Malari (1974), Peristiwa Tanjung Priok (1984), hingga tragedi Trisakti-Semanggi I & 2. Jikalau kita menelusuri sebagian besar peristiwa itu masih belum terungkap dan pelakunya mendapat impunitas (pembebasan dari hukum/kekebalan hukum), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyebutkan diantara peristiwa tersebut dijusitifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity).
Normalisasi dan Diferensiasi
Jika kita membawanya dalam konteks hukum, yang disesalkan dari peristiwa-peristiwa itu adalah penghukuman langsung diberikan secara kontan kepada korban (they took the law into their own hand), dalam peristiwa yang dicap terjadi sedemikian kacaunya dianggap tidak ada hukum seperti penerapan asas legalitas yang ketat dalam pendekatan hukum pidana disebut sebagai due process of law (penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum) dan asas praduga tak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan (Presumption of innocence) untuk mejustifikasi terduga pelaku. Sehingga terduga pelaku berupaya menghindar dari segala macam tuduhan hukum yang datang kemudian hari dengan anggapan situasi yang dicap gaduh tersebut.
Hingga sampai peristiwa itu telah terjadi tidak ada semacam determinasi untuk menyelesaikan hingga menjalankan rekomendasi hasil investigasinya, namun malah terjadi impunitas hingga normalisasi bahwa anggapan peristiwa-peristiwa naas itu hampir dilupakan dan terus menggantung ? hingga kenapa peristiwa-peristiwa itu masih menyisahkan luka sampai sekarang karena enggan untuk diselesaikan. Dalam setiap pemilihan presiden isu terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu itu uterus bergulir dan bergentayangan.
Hal itu berbeda, jika kita membuat semacam diferensiasi dengan kasus-kasus serupa dalam dunia internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan misalnya dalam peristiwa Khmer Merah (1975-1979) dimana pada rezim Polpot terjadi genosida di Kamboja yang diduga menewaskan hampir sekitar 1,7 hingga 2 juta orang, namun peristiwa tersebut mendapat perhatian dan diadili melalui Extra Ordinary Chamber in The Court of Cambodia. Peristiwa perang dunia 2 pun sama, para penjahat perang kemudian diadili dalam Nurmberg Trial yang bertempat di Jerman. Selain itu, peristiwa di bekas negara Yugoslavia dan Rwanda yang menyisakan tidak sedikit korban, dibawah International Criminal Court membentuk badan peradilan ad hoc yang disebut International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia dan International Criminal Tribunal for Rwanda yang eksistensinya adalah menemukan kebenaran dan menyelesaikan kasus-kasus tersebut agar tidak menjadi luka di kemudian hari yang terus menganga.
Penutup
Saya tidak mengatakan diantara kurun waktu 32 tahun masa orde baru itu tidak ada pencapaian positif, malah pencapaiannya cukup signifikan, misalnya pertumbuhan ekonomi, stabilitas dan kesejahteraan. Tapi apakah itu tidak sepadan dengan cost yang dibayarkan dengan dicabutnya kebebasan oleh pemerintah yang otoritarian ? yang selama 32 tahun kuasa militer dan sipil negara dibawah kekuasannya secara absolut ?
Menarik mengutip tulisan Ahmad Fauzi di majalah kompas : bagi sebagian elite, pemimpin orde baru tetap menjadi figur ideal dengan karakter pemimpin yang kuat, paternalistic (figure melindungi dan mengayomi), berhasil menertibkan rakyat dan situasi keamanan. Sementara bagi sebagian rakyat kecil, diingat sebagai masa ketika harga sembako murah dan jalan-jalan dibangun, terjadi swasembada, hingga infrastruktur merata. Kadang perdebatan tentang status pemberian gelar pahlawan nasional itu menjadi terasa rumit dan sumir ketika dikaitkan dengan pencapaian-pencapaian politik semacam ini sehingga keluar kata “sudah wajar mendapat sebuah gelar”.
Namun yang saya tekankan pada tulisan ini adalah bagaimana menyelesaikan fakta-fakta peristiwa masa lalu yang telah banyak disebutkan diatas bisa terselesaikan dan segera setelah itu justifikasi commited by the state oleh pemimpin negara pada peristiwa masa lalu tersebut bisa terehabilitasi bahkan dicabut.













